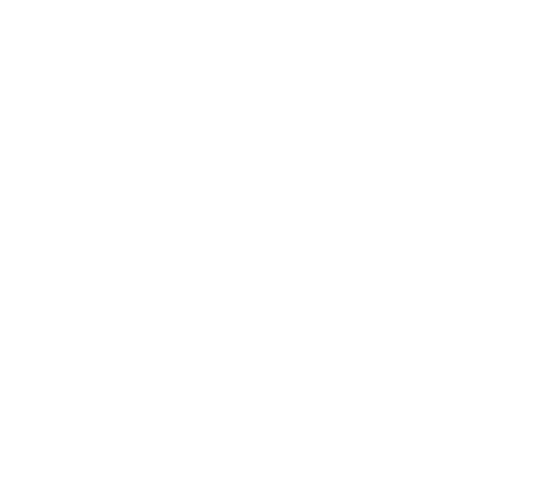Oleh: Fadli Rahman
“Jangan lupa, selalu pakai peci-mu di mana pun kamu berada”
Kata-kata seperti ini sering dijumpai dalam tradisi Pondok Pesantren, sekalipun tidak semua santri memaknai kata-kata dimaksud dalam pengertian yang sama.
Awalnya, bisa jadi pengertian yang didapat atas artikulasi kata-kata di atas adalah pengertian yang bersifat harfiyah, artinya bahwa peci (penutup kepala berbahan beludru warna gelap dengan ketinggian antara 6-12 cm, dan berbentuk lancip di kedua ujungnya) itu adalah sesuatu yang harus selalu dipakai di mana pun, tidak hanya di Ruang Belajar, di Mushalla, di Asrama, Ruang Makan, tapi di mana saja. Bahkan ketika santri terbangun dari tidur malamnya atau istirahat siangnya, yang pertama kali dilakukannya adalah memaki peci-nya, baru selanjutnya melakukan aktivitas lainnya, termasuk juga ketika akan sowan (bertamu) ke tempat seorang kyai di suatu pondok pesantren. Jangan coba-coba sowan tanpa memakai peci, mengapa? Karena akan disuruh pulang, atau setidaknya dipertanyakan – seperti halnya postingan Aan Cogita_Santri dan Peci pada 24 April tahun 2012 dahulu. Pemakaian peci ini lumrah dijumpai di kehidupan para santri yang mondok di pesantren. Hingga akhirnya, peci (dan juga sarung) menjadi identitas mutlak dalam kehidupan pesantren, terutama pesantren-pesantren bernuansa salafi.
Lambat laun, pemaknaan yang bersifat harfiyah seperti halnya ilustrasi di atas mulai mengalami pergeseran manakala santri yang sudah menyelesaikan upaya “nyantri” (belajar agama)-nya di suatu pondok pesantren tersebut mulai bersentuhan dengan dunia luar. Kenyataan bahwa peci (sebagaimana dilansir oleh Alfa RS dalam Pesantren Virtual_Kopiah Identitas Santri?) menjadi identitas Nasional, di mana para pejabat – tanpa melihat suku, agama, ras – ternyata juga memakai peci dalam menjalani tugasnya sebagai pejabat negara, bahkan para perusak negara pun juga ketika “dimejahijaukan” memakai peci sebagai pencitraan atas penyesalan perbuatan dan bersiap diri untuk menjadi orang baik-baik, membuat artikulasi pemakaian peci menjadi ambigu jika hanya dimaknai dalam pengertian harfiyah-nya saja, suatu simbol yang semestinya menyiratkan sebuah sakralitas isi, namun kemudian menjadi tidak bermakna lagi. Dan pada akhirnya, peci bukan lagi difungsikan sebagai identifikasi seorang muslim (bentuk ke-wara’-an ataupun simbol ke-dzuhd-an), pembeda dengan penjajah dan patriotisme (saat penjajahan berlangsung), ataupun nasionalisme (di era Kabinet Bung Karno).
Lebih jauh, Alfa RS mengisyaratkan perlunya penelaahan kembali atas pemaknaan “pemakaian peci” di atas, hingga tidak terjebak dalam artikulasi simbolik dan atribut an sich, yang pada akhirnya justru “menghina” kecerdasan kita sebagai muslim, khususnya kalangan pesantren (manakala “citra” peci tercoreng, maka pesantren pun ikut terkena imbasnya). Bagaimana mungkin cuma dengan modal peci, orang sudah dipercaya “pindah agama”, bagaimana bisa ketaatan beragama dalam semua lini kehidupan hanya muncul dalam bentuk pemakaian peci dan busana muslim/muslimah? Namun sekali lagi – seperti yang diulas dalam Pesantren Virtual tersebut bahwa kita memang masyarakat yang gampang ditipu, apalagi jika tipuan tersebut menggunakan hal-hal yang sakral, simbolik, atributif, seperti halnya peci. Kecenderungan besar kita terhadap atribut, estetika dan sakralitas tertentu mendorong orang lain dengan mudahnya merubah kepribadiannya di hadapan kita. Jika yang bersangkutan telah berdandan sedemikian rupa (sarung, baju koko, dan peci), maka dirasa itu adalah orang yang bertakwa, sama halnya ketika ingin dikira sebagai seniman, orang cukup bermodal memanjangkan rambut dan mengacak-acak dandanannya, “merek” akhirnya mengalahkan “kualitas isi”.
Kembali kepada pemaknaan kalimat di atas: “Jangan lupa, selalu pakai peci-mu di mana pun kamu berada”.Kalimat yang ternyata tidak bisa dimaknai secara harfiyah semata karena relevansinya dengan kehidupan sekarang, saat ini, tidak lagi signifikan. Perlu adanya artikulasi lain yang lebih spesifik, majazi, dan bersifat terminologis, hingga kita tidak lagi terjebak dalam pemaknaan simbolik dan atributif lagi. Di sini, perlu ditinjau terlebih dahulu siapa yang melontarkan kalimat dimaksud, dan kepada siapa kalimat tersebut ditujukan. Tentu, dalam tradisi kepesantrenan, jawabannya adalah kalimat tersebut merupakan wejangan atau petuah dari seorang kyai kepada santrinya, dan bisa jadi hanya kalangan pesantren lah yang sangat memahami artikulasi dan maksud dari kalimat tersebut.
Siapa itu santri? Apakah “santri” hanya dimaknai sebagai seseorang yang mondok di suatu pesantren dalam rangka menimba ilmu agama? Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf – dalam Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di lingkungan Pemda Jawa Barat tahun lalu, sebagaimana diulas dalam Kompasiana.com – menyatakan bahwa Santri adalah orang yang hidup dalam pola kehidupan yang mengamalkan agama Islam dengan sebaik-baiknya, mencintai negeri (hubb al-wathan), dan mau berkorban untuk negara. Sisi utamanya, yaitu kyai, pesantren, dan santri. Tapi, di luar itu semua, ia menyebut bahwa santri adalah masyarakat yang jauh lebih luas dan mengamalkan Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Slamet pun sedikit menyentil pendapat Geertz yang dikatakannya sudah “Jadul” karena mendefinisikan kata Santri sebagai kelompok masyarakat di luar masyarakat Abangan dan Priyayi, karena menyatakan Santri dalam dikhotomi seperti itu sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Sekarang, banyak santri (yang awalnya santri) sudah menjadi pejabat negara, aparat pemerintah, akademisi, tokoh agama,pemuka masyarakat, dan lain-lain, yang di mana pun ia berada, ia diminta oleh kyia-nya untuk selalu memakai “peci”-nya.
Apa maksud dari kata “peci” ini? Dalam sebuah tanya jawab pada Islami.co tahun 2017 silam pernah ditanyakan terkait pemakaian peci ini.
- Santri : “Pak Kyai, Kenapa sih santri harus pake Peci? Kan berat di kepala!”.
- Kyai : “Nah, justru itu. Santri biar terbiasa menundukkan kepala, harus rendah hati(tawadhdhu’) dan tidak sombong”.
Sebuah pertanyaan serius namun disertai dengan alasan iseng, hingga sang Kyai pun menjawab dengan singkat, namun memiliki makna yang mendalam untuk dicermati sekali lagi, dan sekali lagi, dan sekali lagi … (berkali-kali), hingga ketika dikorelasikan dengan pernyataan: “Jangan lupa, selalu pakai peci-mu di mana pun kamu berada”, berarti santri diminta untuk selalu rendah hati, bersifat tawadhdhu’, dan tidak boleh sombong, di mana pun ia berada setelah ia menyelesaikan upaya “nyantri”-nya nanti.
Jawaban Kyai tadi pun semakna dengan artikulasi kata “peci”, baik ditelaah dari sudut pandang ethymologist maupun termynologist-nya. Pengertian “peci” ini pun kemudian mulai diulas dalam jaringan santri.com. Disebutkan di sana bahwa dalam sejarahnya, peci mulai dikenalkan sebagai identitas kebangsaan oleh Bung Karno yang dikenal juga sebagai Pemuda Berpeci sejak pertemuan Jong Java di Surabaya padaJuni 1921, sekalipun sebenarnya yang berperan aktif dalam melestarikan pemakaian peci adalah pondok pesantren dan madrasah. Di lembaga pendidikan Islam tersebut, peci bahkan ada yang dijadikan sebagai seragam resmi. Termasuk juga para tokoh Islam pun memberikan pengaruh untuk menampakkan identitas bangsa Indonesia melalui peci. Beberapa ulama yang berpengaruh terhadap pemakaian peci adalah Kiai Sholeh Darat dan Sayyid Utsman al-Batawi.
Lebih jauh, dalam ulasan tersebut dikatakan bahwa dalam keseharian, kita sering menyebut penutup kepala yang tebuat dari kain berbahan beludru, dan kedua ujungnya berbentuk lancip ini dengan sebutan peci, kopiah atau songkok.
Kata “Peci” muncul di era penjajahan Belanda,kata ini ditulis ‘’Petje’’ yang berasal dari kata ‘’pet’’ (topi) dan “je” yang berarti “sesuatu yang kecil”,penutup kepala yang biasa dipakai oleh bangsa Melayu. Ada hikayat lain yang menyebut peci merupakan rintisan dari Sunan Kalijaga, yaitu “kuluk”atau mahkota sederhana, sebagaimana yang disematkan pada Raden Fattah saat pengukuhan beliau sebagai Sultan Demak.
Adapun kata “kopiah” diadopsi dari Bahasa Arab, “Kaffiyah”. Namun aslinya bentuk kaffiyah yang dari Timur Tengah berbeda dengan kopiah. Kaffiyah merupakan kain penutup kepala berbentuk persegi yang dilipat pada bagian tengah hingga menjadi bentuk segitiga dan berbahan katun. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kopiah itu berasal dari kata ‘’kosong di-pyah’’, yang dalam Bahasa Jawa artinya “kosong dibuang”. Maksudnya, kebodohan, dengki, amarah, dendam,riya’, dan segala sifat buruk manusiawi kita harus dibuang (dalam Tasawuf/Sufism disebut dengan metode Tahally atau Zero Mind Process) dari pikiran dan hati manusia.
Sedangkan kata “Songkok”, dalam kajian sejarahnya berasal dari kata skull cap (batok kepala topi), sebutan oleh pihak Inggris untuk penggunanya di Timur Tengah. sementara di wilayah Melayu, kata tersebut berubah pelafalannya menjadisong kep dan akhirnya disebut Songkok. Namun, ada pula yang menganggap Songkok berasal dari singkatan ‘’Kosong dari Mangkok’’ yang artinya kepala ini seperti mangkok kosong yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan, simpati, empati, kesabaran, pemaaf, ketulusan, dan segala sifat baik lainnya. Dan ini juga mengingatkan kita pada metode lanjutan dalam Tasawuf/Sufism di atas, yakni metode Takhally atau Characters Building. Dan jika kedua metode tersebut telah dijalankan dengan benar, maka akan sampai ke tahap Tajally, di mana semua hal baik yang telah didapat tersebut diimplimentasikan dalam kehidupannya sehari-hari, sesuai dengan kapasitasnya sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.
— Selamat memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2019 —